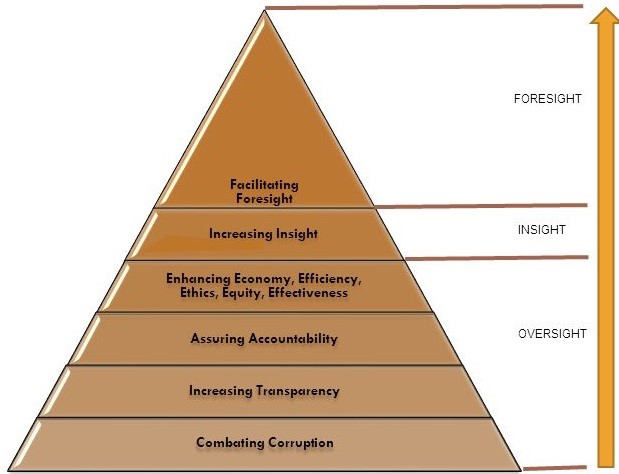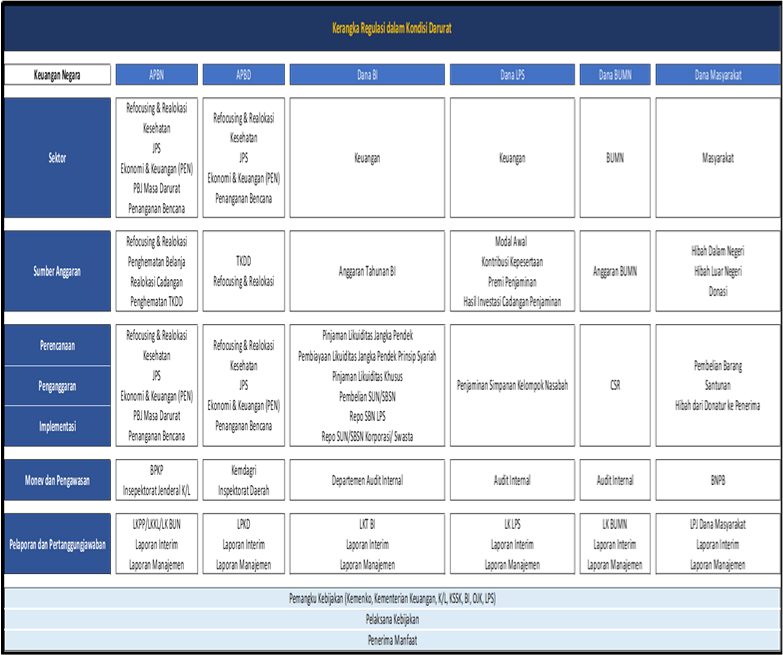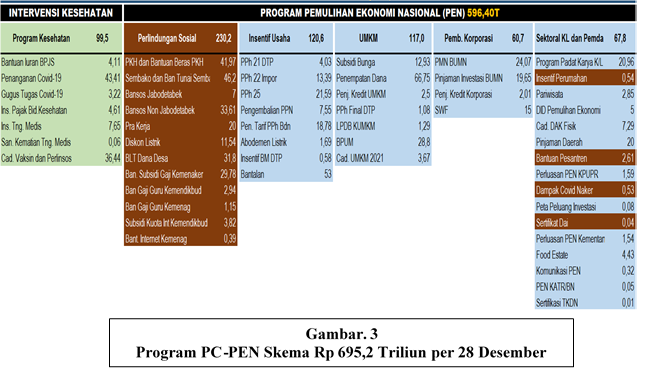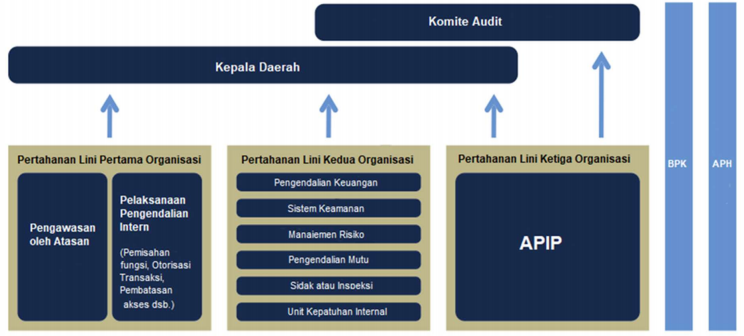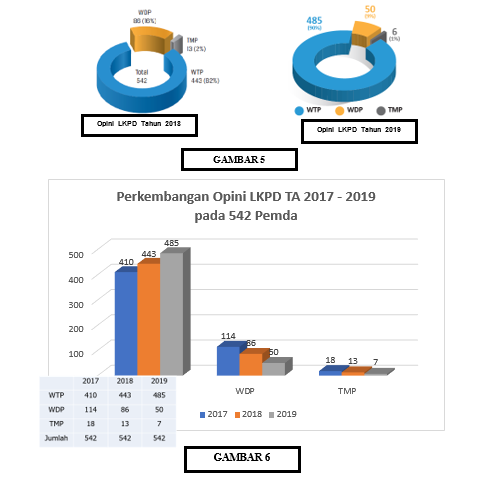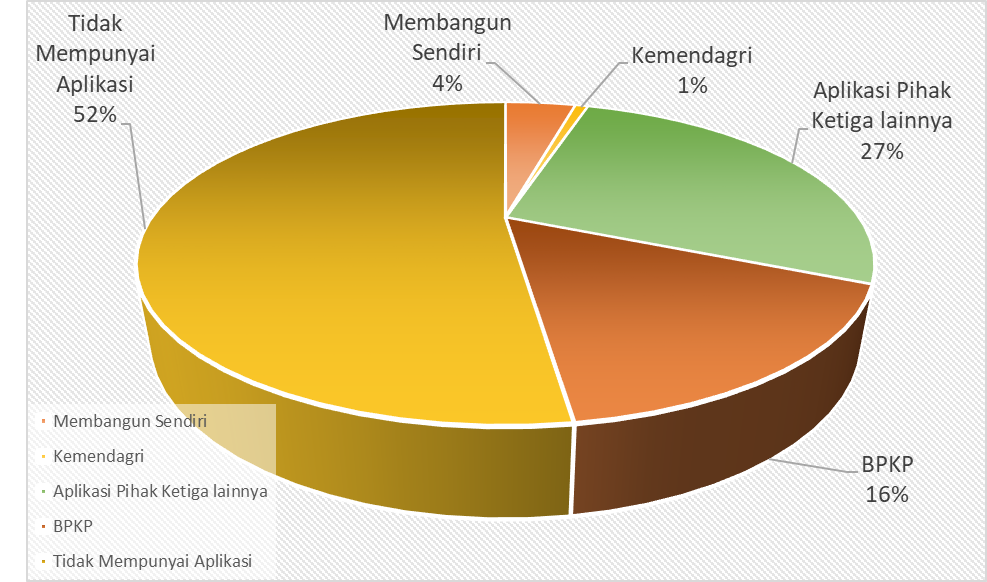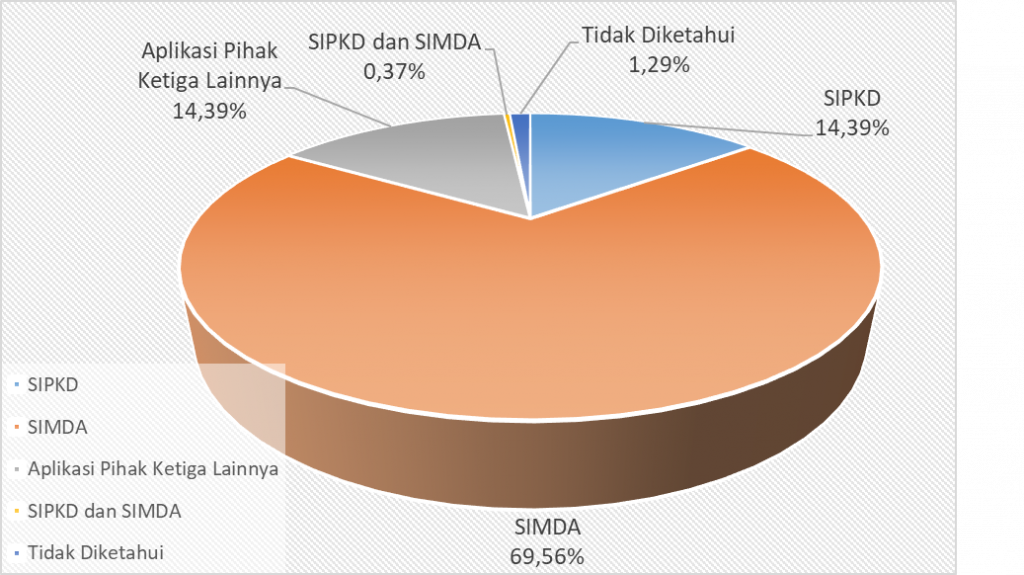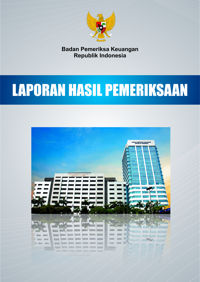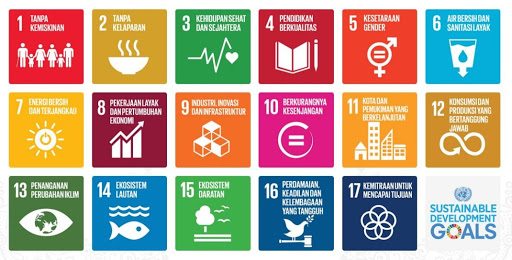Oleh: Eko Yulianto, Pegawai BPK
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan telah menyederhanakan 79 UU yang masih berlaku dan 1.203 pasal menjadi hanya 15 bab dan 186 pasal saja yang mencakup beberapa klaster. Pasal 1 Ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian.
Ruang lingkup UU Cipta Kerja ini meliputi 10 klaster, yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.
Integrasi dan perubahan-perubahan yang dilakukan pada 79 UU menjadi satu UU baru sudah tentu akan memberikan berbagai konsekuensi berupa perubahan peraturan pelaksanaan dan penyesuaian pada 10 klaster tersebut. Termasuk penyesuaian di sektor keimigrasian.
Perubahan UU Keimigrasian
Sejalan dengan asas-asas yang ingin diwujudkan melalui UU Cipta Kerja, perubahan yang dilakukan pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimaksudkan untuk memperluas cakupan pengaturan dan memudahkan kunjungan orang asing yang ingin berkunjung ke dan tinggal di Indonesia. Titik berat dari perubahan-perubahan ini tidak lain untuk semakin memudahkan orang asing dalam berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesa. Ada 8 ketentuan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengalami perubahan melalui UU Cipta Kerja.
Pertama, visa dan izin tinggal saat ini dapat diberikan baik secara manual dan elektronik (Pasal 1 Angka 18 dan Angka 21). Kedua, visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing dalam rangka pra investasi (Pasal 38). Ketiga, Visa Izin Tinggal Terbatas (Vitas) juga dapat diberikan kepada orang asing sebagai rumah kedua (Pasal 39 huruf a) dan penambahan ketentuan huruf mengenai VITAS dimaksud selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 39 huruf c).
Keempat, pemberian Vitas tidak hanya dapat diberikan di perwakilan Indonesia di luar negeri KBRI/KJRI/KDEI (Pasal 40 Ayat (2)). Pemberian visa kunjungan dan Vitas di perwakilan Indonesia di Luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri (Pasal 40 Ayat (3)).
Kelima, penambahan ketentuan ayat terkait orang asing yang mendapatkan izin tinggal terbatas di tempat pemeriksaan imigrasi tidak perlu melapor dan mengajukan permohonan ke kantor imigrasi setempat (Pasal 46 Ayat (4)). Keenam, Izin Tinggal Tetap (Itap) tidak lagi dapat diberikan kepada lansia, namun dialihkan kepada orang asing pemegang ITAS sebagai rumah kedua. Yaitu orang asing beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 54 Ayat (1) huruf a)) dan penambahan ketentuan ayat lebih lanjut mengenai ITAP diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 54 Ayat (4)).
Ketujuh, penambahan ketentuan huruf mengenai penjaminan tidak berlaku bagi pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan (Pasal 63 Ayat (4) huruf b dan huruf c)). Kemudian penambahan ketentuan ayat pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia menyetorkan jaminan keimigrasian sebagai pengganti penjaminan (Pasal 63 Ayat (6)), serta penambahan ketentuan ayat lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan bagi orang asing diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 63 Ayat (7)).
Kedelapan, penambahan ketentuan ayat terkait orang asing yang berada di wilayah Indonesia tidak lagi memperlihat dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya. Melainkan wajib menyerahkannya apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian (Pasal 71 Ayat (1) huruf b)). Kemudian penambahan ketentuan ayat terkait lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 71 Ayat (2)).
Apabila dicermati, beberapa pasal dan ayat serta huruf dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah, ditambahkan, dan dihapus ini menyangkut mengenai pemberian visa dan izin tinggal, serta penjaminan bagi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Termasuk juga penegasan akan adanya peraturan pemerintah atas UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai beberapa perubahan dan penambahan serta penghapusan ketentuan yang ada.
Dari semua perubahan, penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan UU Keimigrasian dalam UU Cipta Kerja ini, yang menarik adalah investor asing dapat melakukan prainvestasi di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Hal ini tentu adalah sebuah inovasi bahwa investor asing dapat menanamkan modalnya tanpa harus terlebih dahulu menggunakan Visa Izin Tinggal Terbatas (Vitas) dengan berbagai persyaratan dan alur birokrasi yang tidak hanya ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Melainkan juga sebelumnya ditujukan kepada beberapa instansi terkait yang berwenang dalam hal perizinan penanaman modal asing.
Hal ini juga sejalan dengan Tri Fungsi Keimigrasian yang salah satunya adalah menjadi fasilitator pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu salah satunya diejawantahkan melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Namun, kemudahan berusaha ini tidak lantas akan menjadikan sebuah “ladang emas” bagi investor asing. Karena Imigrasi akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.
Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Negara
Perubahan pengaturan terkait izin masuk, keluar, dan tinggal di Indonesia bagi orang asing pada UU Keimigrasian memiliki banyak implikasi di bidang hukum, keamanan, sosial, politik, ekonomi dan keuangan negara. Dari sisi keuangan negara, UU Cipta Kerja diharapkan memiliki dampak berupa potensi kenaikan pendapatan negara, baik dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun di balik berbagai manfaat potensial tersebut, UU ini tentu juga memunculkan risiko baru, antara lain yang berhubungan pengelolaan kedua jenis penerimaan tersebut.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan pendapatan sebesar Rp4,303 triliun. Dari jumlah tersebut 59,47% atau Rp2,559 triliun di antaranya berasal dari pendapatan terkait aktivitas keimigrasian. Penjelasannya, terdiri dari pendapatan paspor Rp1,253 triliun, pendapatan visa Rp406,73 miliar, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali Rp716,93 miliar, dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya Rp182,20 miliar. Dengan berbagai kelonggaran dalam hal kunjungan dan izin tinggal di Indonesia bagi orang asing, pendapatan yang dikumpulkan oleh Ditjen Imigrasi besar kemungkinan akan mengalami kenaikan, khususnya pada tiga pos yang disebut terakhir.
Dibandingkan dengan pendapatan negara dari sektor pajak, perolehan PNBP tersebut barangkali tidak signifikan. Namun dampak ikutan dari banyaknya orang asing yang mengunjungi, tinggal dan berinvestasi di Indonesia jelas memiliki signikansi tersendiri. Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia menjadi salah satu sumber penggerak perekonomian sektor pariwisata. Investasi asing di Indonesia akan berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan baru yang dapat mendorong kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak.
Sampai akhir 2019, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan asing di Indonesia adalah 16,11 juta. Sementara itu, nilai investasi asing selama 2019 tercatat sebesar 28.208,8 juta dolar AS. Pemerintah berharap, hadirnya UU Cipta Kerja pada akhirnya akan mampu meningkatkan kedatangan wisatawan maupun investasi di Indonesia. Namun sejauh ini belum ada analis yang memperkirakan besaran peningkatannya karena peraturan pelaksanaan UU tersebut saat ini masih dalam penggodokan.
Sistem Informasi Keimigrasian
Terlepas dari berbagai perkiraan dampak yang akan ditimbulkan pada tahun-tahun yang akan datang, satu hal yang pasti dari UU Cipta Kerja ini adalah kenaikan arus masuk orang asing. Baik untuk keperluan kunjungan, tinggal dan berusaha di Indonesia. Dalam konteks ini, manajemen data kunjungan orang asing melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menjadi titik yang paling krusial. Karena di samping manfaat, kemudahan akses orang asing ke Indonesia juga mengandung risiko yang dapat menimbulkan permasalahan sosial dan keamanan. Di samping itu, pengelolaan keuangan negara terkait keimigrasian juga sangat bergantung dengan manajemen data tersebut.
Dalam kaitan manajemen data tersebut, pertanyaan terpenting yang harus terjawab adalah apakah Ditjen Imigrasi telah memiliki sebuah sistem informasi terpadu yang efektif mampu menampilkan data akurat menyangkut orang asing yang telah masuk ke, sedang berada di, dan telah keluar dari Indonesia? Sistem informasi tersebut menjadi landasan penting untuk pengelolaan aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan keuangan negara. Sistem informasi tersebut antara lain harus mencakup pengelolaan data perlintasan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan penerimaan negara.
Dalam kaitan ini, UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur bahwa Direktur Jenderal Imigrasi bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (disingkat SIMKIM) sebagai sarana pelaksanaan fungsi keimigrasian di dalam atau di luar wilayah Indonesia. SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. SIMKIM merupakan satu kesatuan dari berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk menyatukan dan menghubungkan sistem informasi pada seluruh pelaksana fungsi keimigrasian secara terpadu. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Kelemahan SIMKIM
Seperti telah disinggung sebelumnya, pertanyaan kunci mengenai pengelolaan data keimigrasian berbasis SIMKIM adalah apakah sistem ini mampu merekam dan menyajikan data orang asing yang telah masuk, tinggal, dan meninggalkan Indonesia secara akurat. Akurasi data ini sangat penting karena akan menjadi basis penghitungan penerimaan negara dari sektor keimigrasian dan bahan pembuatan keputusan penting lainnya. Jika SIMKIM tidak mampu memenuhi tujuan manajemen data tersebut, maka pemerintah berpotensi menerima berbagai konsekuensi mulai dari kerugian keuangan negara sampai dengan persoalan keamanan dalam negeri.
Dari aspek keuangan negara, ketidakakuratan data SIMKIM akan berakibat pada kekurangan penerimaan PNBP sektor keimigrasiaan, yang juga berarti kerugian keuangan negara. Kekurangan penerimaan tersebut bisa terjadi karena sebab-sebab berikut.
Pertama, data keimigrasian tidak lengkap. Terlepas dari tujuan keberadaan SIMKIM, potensi ketidaklengkapan data keimigrasian masih mungkin terjadi. Kelengkapan dan keakuratan data orang asing yang mengunjungi Indonesia akan bergantung pada rancangan dan pengoperasian aplikasi, khususnya terkait dengan proses perekaman dan pengintegrasian data kunjungan. Dari sisi keuangan negara, kegagalan SIMKIM dalam mengintegrasikan data kunjungan tentu berdampak pada ketidaktepatan penghitungan penerimaan PNBP dari visa dan izin tinggal.
Kedua, data keimigasian tidak mutakhir. Di samping, ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data lalu lintas orang asing yang masuk ke dan keluar dari Indonesia, permasalahan juga bisa terjadi terkait kemutakhiran data orang asing yang tinggal di Indonesia. Apabila SIMKIM tidak mampu menampilkan data orang asing yang izin tinggalnya sudah melewati waktu yang diizinkan, dari sisi keuangan negara, risiko utamanya adalah tidak dapat diterimanya pendapatan dari izin tinggal, di samping potensi permasalahan sosial lainnya.
Sejauh ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum memiliki informasi mengenai keefektifan SIMKIM dalam menyediakan data akurat mengenai keberadaan orang asing di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan terkait SIMKIM setidaknya telah terungkap ke publik menyusul terungkapnya masalah tidak terdeteksinya keberadaan Harun Masiku, seorang anggota DPR, yang telah kembali ke Indonesia dari luar negeri.
Pokok permasalahannya adalah data kedatangan yang bersangkutan ternyata tidak terdeteksi karena proses pemutakhiran atau sinkronisasi data SIMKIM tertunda dengan alasan yang belum diketahui. Persoalan ini menjadi sangat signifikan karena hal ini tidak hanya menyangkut anggota DPR, melainkan data lalu lintas 120 orang di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.
Penulis berpendapat, bahwa gambaran satu kasus terkait pengelolaan data SIMKIM tersebut setidaknya cukup memberi gambaran mengenai kelemahan pemantauan perlintasan orang masuk ke dan keluar dari Indonesia. Sampai saat ini pun, kita belum mengetahui apakah hal sama pernah terjadi di pintu masuk lainnya yang tersebar di bandara atau pelabuhan di seluruh Indonesia. Kita juga belum mengetahui secara pasti apakah persoalan terkait SIMKIM hanya soal itu. Namun demikian, satu hal yang pasti, ketidakberesan pengelolaan SIMKIM akan memunculkan risiko serius dari aspek keamanan dalam negeri, di samping risiko keuangan negara.
Kesimpulan
Tulisan ini secara singkat telah memaparkan bahwa UU Cipta Kerja telah menghadirkan risiko yang lebih besar dari berbagai aspek, termasuk keuangan negara, khususnya dari klaster imigrasi. Bila dicermati, risiko sebenarnya sudah ada sebelum UU Cipta Kerja diundangkan. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai risiko keuangan negara pada klaster keimigrasian tidak dapat dilepaskan pada akurasi data lalu lintas orang masuk ke dan keluar dari Indonesia.
Dari data yang ada, penulis berpendapat bahwa risiko ketidakakuratan data imigrasi sudah ada sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan. Hal ini terkait dengan kelemahan SIMKIM yang digunakan Ditjen Imigrasi saat ini. Risiko tersebut akan semakin besar pasca-UU Cipta Kerja karena kedatangan orang asing ke Indonesia untuk berwisata, tinggal, dan berinvestasi akan semakin mudah.
Dengan kata lain, UU Cipta Kerja akan memperbesar lalu lintas orang asing di Indonesia. Oleh karena itu, jika kelemahan SIMKIM tidak segera diatasi maka dampaknya pada aspek keuangan negara dan aspek lainnya tidak dapat dikendalikan.
Berangkat dari fakta belum adanya informasi menyeluruh mengenai keefektifan SIMKIM dalam mengelola data perlintasan orang masuk ke dan keluar dari Indonesia, pemeriksaan kinerja terkait SIMKIM akan lebih baik apabila segera dilakukan. Alasan utamanya adalah semakin besarnya risiko yang dihadapi Indonesia pasca-UU Cipta Kerja. Pengelolaan data lalu lintas dan keberadaan orang asing di Indonesia merupakan hal yang sangat krusial, karena tidak saja menyangkut persoalan keuangan negara, melainkan juga keamanan dalam negeri.